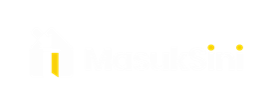Sekolah Membunuh Kreativitas Anak dengan Menyuruh Menggambar Dua Gunung, Sawah dan Matahari
Ketika mencicipi mata pelajaran Geografi untuk pertama kalinya di bangku SMP, saya selalu senang ketika Pak Guru mulai meminta kami membuka atlas seraya beliau bergerak dari papan tulis menuju peta dunia yang tergantung di dinding. Melihat luasnya dunia dalam lembaran-lembaran kertas memang menakjubkan, terlebih lagi ada satu hal yang selalu membuat saya penasaran: bagaimana bentuk benua Afrika bisa begitu cocok jika disandingkan dengan Amerika Selatan, seperti puzzle.
Setelah sekian lama menyimpan rasa penasaran, saya pun memberanikan diri untuk bertanya pada Pak Guru:
“Pak, kenapa Afrika dan Amerika Selatan punya kecocokan di salah satu sisinya? Apa mereka dulu satu benua?”
Bukannya langsung memberikan jawaban, beliau terbahak-bahak — mungkin karena menganggap pertanyaan saya lucu.
“Mana mungkin dua benua yang berbeda pernah bersatu? Gak pernah ada, Nak!”
Saya pun mengangguk saja, karena sebagaimana yang selalu diajarkan pada saya, guru adalah orang yang paling benar.
Baru bertahun-tahun kemudian saya membaca tentang Pangaea, sebuah benua super yang terbentuk 300 juta tahun yang lalu. Benua tersebut mulai pecah dan bergeser 100 juta tahun yang lalu hingga membentuk bumi seperti sekarang. Nyatanya, benua Afrika dan Amerika Selatan memang pernah bersatu membentuk Pangaea.
Pertanyaannya: kenapa sah-sah saja menurut Pak Guru untuk menertawai rasa penasaran muridnya (yang toh ternyata berdasarkan fakta!), dan kenapa pula saya bisa sangat percaya bahwa menghormati Guru adalah segalanya?
Mungkin Tujuan Sekolah Bukanlah Untuk Mendidik Kita Jadi Pintar, Melainkan Mencetak Manusia yang Gampang Diatur dan Sesuai Standar — Seperti Robot

Bukan salah guru Geografi saya sepenuhnya jika beliau belum pernah mendengar nama Pangaea. Mungkin ia terlalu fokus pada materi kurikulum sehingga tak sempat mengeksplor materi Geografi yang ada di luar buku teks. Yang saya sesalkan adalah beliau menganggap menertawakan imajinasi yang ditelurkan peserta didiknya sebagai hal yang sah-sah saja.
Berapa menit sih yang akan terbuang di kelas jika Pak Guru meminta saya menjelaskan mengapa saya bisa punya pertanyaan demikian? Padahal, dengan senang hati saya akan menunjukkan betapa cocoknya garis benua di sisi barat Afrika dengan sisi timur Amerika Selatan. Bukan hal mengejutkan bila pembaca juga pernah mengalami kejadian serupa dengan saya di bangku sekolah. Atau justru pembaca takut untuk bertanya pada guru, karena sudah dididik sedemikian rupa untuk terbiasa menerima — tanpa banyak bertanya?
Bisa jadi, sistem pendidikan yang saat ini ada tidak dirancang untuk membuat anak-anak didiknya menjadi ingin tahu dan pintar. Mungkin sistem pendidikan ini lebih bertujuan melatih semua anak didik untuk bisa memenuhi suatu standar: standar tentang apa itu murid teladan.
Di Indonesia, murid teladan bukanlah mereka yang rajin membaca, ingin tahu, dan berani bertanya atau mendebat guru. Murid teladan adalah mereka yang “patuh”, “kalem”, “sopan”. Murid teladan adalah mereka yang bisa menaati standar:
1. “Sopan”, patuh dan penurut pada apapun kata guru (sementara banyak murid punya rasa ingin tahu yang luar biasa dan pemikiran yang kritis)
2. “Kalem”, tidak banyak tanya. Belajar dengan mencatat pelajaran secara seksama (sementara banyak murid bisa menyerap ilmu dengan maksimal justru jika dibolehkan berdiskusi)
3. “Rapi”, dengan panjang rambut hingga warna sepatu yang sudah ditentukan dan tak dapat dibantah
4. Punya bakat di bidang Matematika dan IPA. (Bakat lain seperti menulis dan bermusik adalah nilai plus, namun bakat di bidang sains adalah permata yang menjadikan mereka lebih pintar dari murid-murid lainnya)
Murid yang tak bisa memenuhi standar ini adalah “nakal”, “bandel”, atau “bodoh”.
Memberlakukan standar sebenarnya bukan hal yang haram. Bukankah dengan ini para birokrat bisa mengukur perkembangan dunia pendidikan? Namun, apakah standar ini kemudian harus mengorbankan jiwa kreatif anak-anak kita? Apakah standar ini harus membunuh kepribadian unik yang dimiliki masing-masing mereka?
Saat Masih TK/SD, Kita Selalu Menggambar Gunung Kembar Dengan Matahari dan Sawah. Kenapa Sekolah Tak Mendorong Kita Berani Beda?

Berapa banyak di antara kita yang menggambar sepasang gunung dengan matahari mengintip di tengahnya, serta aliran sungai atau jalan yang membelah sawah di bawahnya? Hampir semua anak Indonesia yang pernah sekolah pernah menggambarnya. Kenapa?
Padahal, tidak semua anak Indonesia hidup di dekat area persawahan. Tidak semua dari kita beruntung punya tempat tinggal dengan pemandangan gunung kembar. Secara emosional, mungkin kita lebih dekat pada pantai, perbukitan tandus, atau bahkan lampu-lampu kota — karena itulah yang sering kita lihat sehari-hari.
Tetap saja kita merasa wajib menggambar gunung dan sawah. Karena semua teman kita menggambar pemandangan yang sama, kita takut beda sendiri. Lagipula, arena guru kita tak pernah membebaskan murid-muridnya untuk menggambar objek lain.
Setiap manusia lahir dengan kreativitas natural masing-masing, namun sekolah membunuh kreativitas anak. Anak dilatih untuk merasa malu saat ingin melakukan hal yang berbeda dari teman-temannya. Kepribadian mereka yang unik sengaja ditekan. Kalau tidak bisa? Katakan mereka bandel. Katakan mereka nakal. Katakan mereka susah diatur!